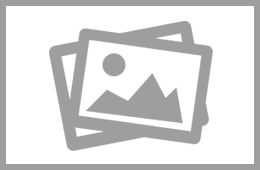Secara sederhana, antropologi
dapat diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang
manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman dan lain sebagainya. Sedangkan
kebudayaan itu sendiri merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang
dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya
dengan belajar.[1]
Kebudayaan bukanlah benda mati atau statis, ia
akan selalu berubah baik karena dorongan internal
maupun eksternal. Secara internal, perubahan budaya disebabakibatkan oleh variasi-variasi baru dalam sebuah kebudayaan kedalam buah tingkah-laku yang dikenalkan dan disosialisakikan baik itu oleh individu ataupun kelompok masyarakat, sehingga pada akhirnya perilaku tersebut dikemudian hari menjadi milik bersama,
dan selanjutnya menjadi bagian dari sebuah kebudayaan. Sedangkan faktor eksternal kebudayaan dapat juga terjadi karena beberapa aspek dalam lingkungan kebudayaan telah mengalami perubahan hingga
akhirnya membuat kebudayaan itu lambat laun menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
Kampus adalah ruang akademik dan sebagai menara gading mahasiswa dalam menempuh proses pendewasaan diri dalam kultur ilmiah dan diskursif wacana pengetahuan. Dalam proses dunia kampus itu sendiri, ternyata sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Karena kampus dalam realitanya adalah
menjadi pusat aktivitas para anggota masyarakatnya yang menghasilkan berbagai
aneka hasil budinya seperti ide-ide, gagasan-gagasan, pola pikir, pola rasa,
pola perilaku, norma-norma, adat kebiasaan dan nilai-nilai insani, serta karya
lain yang dapat dinikmati, mendewasakan dan memberdayakan anggota masyarakatnya
untuk lebih berkualitas dan lebih mengerti tentang dunia dan kehidupan yang
selalu menyertainya. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat kampus yang
mempunyai peran dan tanggungjawab dalam menciptakan dinamikan dan realitas
ideal dalam dunia kampus.
Mengapa demikian? Karena mahasiswa adalah menjadi harapan besar bagi masyarakat sebagai pembawa
perubahan dilingkungannya masing-masing. Oleh karenanya, mahasiswa dituntut untuk mengimplementasikan berbagai macam sikap, perilaku yang arif, serta daya pikiran progresif kedalam sebuah bentuk
yang konkrit, bukan perilaku
dan pikiran yang melulu abstrak dan
teoretis ansich. Dalam artian ini bahwa mahasiswa itu tidak
hanya ‘melangit’ secara teoretis, tetapi juga dibutuhkan pemikiran
dan gerakan yang ‘membumi’ dalam hal praksis. Atau
dengan ungkapan lain, mahasiswa tidak hanya menjaga tradisi baik yang ada (al-mukhafadah’ala
al-qadim ash-shalih), namun juga harus berpikir kreatif dan mengakomodir
realitas kontemporer yang baru yang lebih baik (al-akhdzu bi al-jadid
al-aslah),[2] atau lebih singkatnya bahwa mahasiswa itu harus berpegang pada
pemahaman dalam hal mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru
yang lebih baik,[3]
serta menuangkan ide-ide kreatif untuk bisa
dimanfaatkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Apa yang perlu diperbaiki
dari yang sudah ada, atau melakukan perubahan yang bisa lebih bermanfaat bagi
masyarakat dan bangsa.
Tidak dapat
dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu
ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, sehingga
kaderisasi harus dilakukan secara terus-menerus. Dunia kampus dan dunia kemahasiswaan
(organisasi)
merupakan momentum kaderisasi yang sangat
sayang bila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalankan dengan penuh tanggung
jawab bagi mereka (mahasiswa) yang memiliki
kesempatan.
Melemahnya pergerakan mahasiswa salah satunya adalah dilatarbelakangi oleh
melemahnya budaya literasi dikalangan mahasiswa itu sendiri, yang pada akhirnya
membuat kritisme pemikiran terhadap keadaan sekelilingnya pun turut melemah.
Budaya literasi yang dimaksud adalah membaca, menulis dan berdiskusi.
[1] Koentjaraningrat, Pengantar
Antropologi, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 72.
[2] Hal ini sesuai dengan paham keagamaan yang
dianut NU, yang tersimpul dalam sebuah kaidah yang populer, yaitu al-mukhafadhah
‘ala al-qadim ash-shalih wal al-akhdzu bi al-jadid al-aslah. Ahmad Zahro, Tradisi
Intelektual NU,
(Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 21.
[3] Nurcholis Madjid, Islam Agama
Kemanusiaan, Cet. II, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. vii.