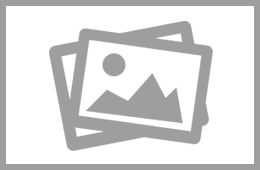Prawacana
Sifat
inferioritas yang telah dilekatkan oleh tradisi (turats) kepada perempuan bahwa mereka adalah kurang dalam hal akal,
dan agama hanyalah pandangan yang mengada-ada yang telah ditetapkan oleh sistem
masyarakat patriarkis yang berlaku
saat itu.[1]
Seperti
yang diungkapkan oleh Shahrur di atas bahwa pengaruh budaya patriarki telah membentuk stereotip dan paradigma kultural yang
merendahkan, melecehkan dan menyebabkan perspektif misoginistik terhadap kaum perempuan. Semua itu telah menjadi
tradisi yang begitu mengakar, sehingga menjadi tugas yang sulit dan berbenturan
dengan banyak kendala untuk menghapuskan disparitas
subordinatif kaum perempuan dari laki-laki.
Isu gender menguat ketika disadari
bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan
telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau
pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak
penting dalam urusan politik, stereotype
atau pencitraan negatif bagi perempuan.
Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut
3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan dan double
burden
(beban ganda) terhadap perempuan yang
bermuara pada perbuatan
tidak adil yang dibenci oleh Allah Swt.
Gerakan
perubahan yang terjadi masa sekarang dan masa-masa mendatang lebih mengutamakan
persamaan antara kedua jenis laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai baru telah
tumbuh bersamaan dengan desakan teknologi modern, sehingga muncul peradaban
yang mendorong pembebasan beban historis yang dipikul kaum perempuan. Dalam
konteks kekinian, banyak sektor strategis yang menuntut ketelibatan perempuan,
mengingat mereka memiliki kemampuan dalam bidang dan jasa tertentu yang bagi
laki-laki mungkin sulit untuk melakukannya.
Harus
pula dipahami bahwa fakta tersebut di atas, akan sangat menarik jika
dihubungkan dengan al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam. Sebab misi
utama al-Qur’an adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki,
ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Qur’an pada dasarnya sangat bijak berbicara tentang
masalah gender dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan.
Al-Qur’an tidak pula menafikan adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan,
tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan salah satu
pihak dan merugikan pihak lain.
Jika
di lihat dari segi historis, al-Qur’an merupakan sumber nilai yang pertama kali
menggagas konsep keadilan gender. Di antara kebudayaan dan peradaban dunia yang
hidup pada masa turunnya al-Qur’an seperti Yunani, Romawi, Yahudi, Persia,
China, India, Kristen dan Arab (pra-Islam), tidak ada satupun yang menempatkan
perempuan lebih terhormat dan lebih bermartabat daripada nilai-nilai yang
diperkenalkan oleh Qur’an.
Berangkat
dari hal tersebut, setidaknya ada dua pertanyaan yang muncul ketika mencermati
topik di atas yaitu; Pertama, apakah yang dimaksud dengan kesetaraan
gender? Kedua, bagaimana persoalan ini dilihat dari teks dan konteks di
hubungkan dengan nash al-Quran.
A.
Pengertian Gender dan
Perbedaannya dengan Sex
Istilah "gender" berasal dari
bahasa Inggris "gender" yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus
Webster diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara lelaki dan perempuan
dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. H.T. Wilson mengartikan gender
sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan
perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka
menjadi laki-laki dan perempuan. Singkatnya, menurut Nasaruddin, gender
merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan
laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini
mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.[2]
Terdapat perbedaan yang jelas antara gender
dan sex. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan
laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya, maka istilah sex secara umum
dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi
anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi
seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi
fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sex juga merupakan jenis kelamin biologis ciptaan Tuhan, seperti perempuan
memiliki vagina, payudara, rahim, bisa melahirkan dan menyusui sementara
laki-laki memiliki jakun, penis, dan sperma, yang sudah ada sejak dahulu kala.
Sedangkan gender menyangkut perbedaan fungsi, dan peran Sedangkan gender
lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek
non biologis lainnya.[3]
Berikut tabel perbedaan
antara gender dengan sex:
|
Gender
|
Sex (Jenis Kelamin)
|
|
·
Dapat berubah
·
Dapat dipertukarkan
·
Tergantung musim
·
Tergantung budaya
masing-masing
·
Bukan kodrat (buatan
masyarakat)
|
·
Tidak dapat berubah
·
Tidak dapat
dipertukarkan
·
Berlaku sepanjang masa
·
Berlaku dimana saja
· Kodrat (ciptaan
Tuhan); perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui
|
Dari penjelasan mengenai gender dan sex tersebut
di atas, dapat dipahami bahwa sex merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan
dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil
konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau
perempuan.
Perbedaan tersebut penting untuk diungkapkan,
karena banyak persepsi yang bias dan tidak membedakan antara gender dan sex.
Banyak masyarakat yang memahami bahwa atribut biologis pada seseorang seperti
penis pada lelaki dan vagina pada perempun, maka hal itu akan menjadi identitas
gender bagi yang bersangkutan dan akan menentukan peran sosial dalam
masyarakat. Padahal relasi gender tidak didasarkan pada faktor biologis, melainkan
pada kualitas, skil dan konvensi-konvensi sosial.
B.
Perspektif Gender
dalam Penafsiran al-Qur’an
Al-Qur`an, menurut Asghar Ali Engineer,
seorang feminis Muslim dari India, secara normatif menegaskan konsep kesetaraan
status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyarakatkan
dua hal. Pertama, dalam pengertiannya yang umum, yaitu penerimaan
martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang
harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara
dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, keduanya memiliki hak yang setara
untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya memiliki hak
untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, keduanya
bebas memilih profesi atau cara hidup, dan keduanya juga setara dalam tanggungjawab
sebagaimana dalam hal kebebasan.[4]
Dalam beberapa ayat al-Qur`an, masalah
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini mendapat penegasan. Secara umum
dinyatakan oleh Allah Swt dalam Surat al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia,
tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang
bersifat given lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Mulia
dan tidaknya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah
prestasi yang dapat diusahakan. Secara khusus kesetaraan laki-laki dan perempuan
itu ditegaskan oleh Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 35, yang artinya:
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang
muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min, laki-laki dan perempuan yang tetap
dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama)
Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzab:35)
Namun demikian, dalam beberapa ayat yang
lain, muncul problem kesetaraan, terutama dalam penafsiran terhadap teks-teks
tersebut. Misalnya, problem kesetaraan muncul dalam masalah penciptaan
laki-laki (Adam As) dari tanah, sementara perempuan (Hawa) dari tulang rusuk
Adam. Dalam tugas-tugas keagamaan problem kesetaraan muncul mulai dari tidak
adanya perempuan jadi Nabi, dan tidak bolehnya perempuan mengimami jama’ah
laki-laki dalam shalat, atau jadi khatib shalat Jum’at dan ‘Iedain (penafsiran
terhadap ayat-ayat tentang shalat berdasarkan hadits Nabi), bahkan kaum
perempuan tidak dibolehkan shalat selagi mereka haidh.
Dalam perkawinan muncul problem kesetaraan
dalam masalah perwalian (perempuan harus menikah dengan wali), perceraian (kenapa
hak menjatuhkan talak hanya ada pada laki-laki), poligami (laki-laki boleh
poligini sedangkan perempuan tidak boleh poliandri), nikah beda agama (kenapa
laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara perempuan
Muslimah tidak diizinkan menikah dengan laki-laki non Muslim manapun, termasuk
dengan Ahlul Kitab).
Dalam bidang lain juga muncul problem
kesetaraan dalam masalah pembagian warisan (anak laki-laki dapat dua bagian
anak perempuan), kesaksian dalam transaksi kredit (formula dua saksi laki-laki
atau satu laki-laki dua perempuan), dan juga problem kesetaraan muncul dalam
masalah pembagian tugas publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan.
Problem kesetaraan di atas, dapat diatasi
dengan menafsirkannya secara kontekstual. Karena secara konstektual, al-Qur`an
memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan.
Tetapi dari beberapa mufassir dengan mengabaikan konteksnya, dan ini sangat
disayangkan. Metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat
teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir
menggunakan sosio-teologis.[5]
Sebab satu cara untuk menghindari penafsiran yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan adalah dengan pendekatan kontekstual.
Tapi sebelumnya harus di diskusikan lebih dahulu apakah bentuk sebuah
penafsiran bersifat diskriminatif sehingga perlu ditafsirkan secara
kontekstual. Dalam kasus kepemimpinan rumah tangga misalnya, menafsirkan teks
kepemimpinan suami atas istri dalam rumah tangga apa adanya secara tekstual
(dengan argumen yang disebutkan sendiri oleh teks itu), apakah bersifat
diskriminatif yang dengan sendirinya bertentangan dengan ide tentang
kesetaraan, atau memang sudah seharusnya demikian dengan alasan-alasan yang
rasional dan realistis? Apakah kesetaraan harus diartikan bahwa segala sesuatu
harus sama? Tidakkah posisi pemimpin dan yang dipimpin atau status struktural
tersebut hanyalah sesuatu yang bersifat fungsional semata, yang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan persoalan kesetaraan, sebab kesetaraan menyangkut
nilai yang esensi misalnya adalah kemanusiaan.
Jadi, perspektif gender memang diperlukan
dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an, terutama dalam masalah perempuan, dalam
hubungannya dengan laki-laki. Tetapi baik para mufassir maupun para
pengkritiknya dari kalangan feminis haruslah berusaha sama-sama menjaga
kejernihan cara pandang, sehingga masing-masing tidak terjebak dari bias-bias
yang tidak diperlukan.
C.
Identitas Gender
dalam al-Qur’an
Dalam al-Qur’an, terdapat beberapa kata yang
berkonotasi laki-laki dan perempuan, seperti al-rajul, al-dzakar, al-mar' dan al-nisa, al-untsa serta al-mar'ah. Dari kata-kata tersebut, ada distingsi
makna yang signifikan di antara berbagai istilah tersebut. Bila kata al-rajul, al-nisa, al-mar' dan al-mar'ah
digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, telah berumah
tangga atau telah mempunyai peran tertentu dalam masyarakat.
Semua kata tersebut dipakai manakala memenuhi
kriteria sosial dan budaya tertentu, termasuk mempunyai kecakapan bertindak
atau skil; untuk hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender.
Sedangkan istilah al-dzakar dan al-untsa hanya menunjukkan jenis kelamin
laki-laki dan perempuan secara biologis tanpa dikaitkan faktor kedewasaan atau
kematangan yang bersangkutan. Dengan demikian, semua kata al-rajul dan al-nisa
misalnya, mencakup kategori al-dzakar
dan al-untsa. Tapi tidak semua al-dzakar dan al-untsa meliputi kategori al-rajul
dan al-nisa.
Pada titik inilah, khithab (perintah dan larangan) Tuhan yang menggunakan kata al-dzakar dan al-untsa yang mengacu kepada faktor biologis lebih mudah dipahami
karena identitas biologis lelaki dan perempuan mempunyai ciri-ciri universal,
sedangkan khithab Tuhan yang
menggunakan kata al-rajul, al-nisa atau
al-mar'ah memerlukan pemahaman lebih kontekstual karena identitas gender
banyak dipengaruhi faktor budaya, sementara budaya setiap masyarakat mempunyai
kekhususan-kekhususan.
Melalui paradigma di atas, maka kata al-rijal, misalnya, dalam ayat yang
menyatakan: Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. Dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan dari
pada istrinya (Qs 2: 228), merupakan laki-laki tertentu yang mempunyai
kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih
tinggi daripada perempuan. Kerena itulah, Tuhan tidak menggunakan kata al-dzakar (wa lidzakari), sebab jika
demikian secara alami berkonotasi bahwa semua lelaki memiliki tingkatan lebih
tinggi ketimbang perempuan.[6]
D.
Konsep Gender dalam
al-Quran
Terdapat lima variabel yang dapat digunakan
sebagai standar untuk menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an.
Pertama, laki-laki dan perempuan
sama-sama sebagai hamba. Ayat al-Qur’an yang bisa dijadikan justifikasi yaitu
surat al-Zariyat ayat 56: Dan Aku tidak
menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepada-Ku.
Dalam kedudukannya atau kapasitas manusia
sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Keduanya
mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yang biasa
diistilahkan al-Qur’an dengan orang-orang yang bertaqwa (muttaqun). Bahkan untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa
atau kelompok etnis tertentu (Qs 49: 13).[7]
Kedua, laki-laki dan
perempuan sebagai khalifah di bumi. Selain menjadi hamba yang tunduk dan patuh
serta mengabdi kepada Allah, maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi
adalah untuk mengemban amanah sebagai pemimpin (khlifah fi al-ardl). Postulat yang menjadi pijakan mengenai hal
tersebut yaitu surat al-An'am: 165: Dan
Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan
sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu
tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian.
Sebenarnya banyak cerita sukses kaum wanita
dalam mengemban amanah sebagai pemimpin. Dalam investigasi
historis-sosiologisnya, Fatima Mernisi menemukan 15 penguasa perempuan di
berbagai wilayah Muslim antara abad 13 sampai 17. 2 (dua) orang penguasa Turki
yaitu Sultanah Radiyyah dan Sultanah Syajarat al-Durr; 6 (enam) orang dari
lingkungan penguasa Mongol; 3 (tiga) ratu pada entitas politik Islam di
Maldives; serta 4 (empat) ratu dari kerajaan Aceh, yakni Sultanah Taj al-Alim
Sufiyyah al-Din Syah, Sultanah Nur Alam Nakkiyah al-Din Syah, Sultanah Inayah
Syah dan Sultanah Kamalat Syah.[8]
Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima
perjanjian primordial. Baik laki-laki dan perempuan keduanya mendapatkan
perjanjian primordial dari Tuhan. Al-Qur’an mendeskripsikan perjanjian tersebut
saat manusia berada dalam rahim, dalam keadaan pra-eksistensial: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?"
Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi".
(Qs. 7: 172)
Tidak seorang anak manusia pun lahir di muka
bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan dan ikrar mereka disaksikan
para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak" sehingga
dalam Islam tanggungjawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini.
Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal diskriminasi jenis kelamin.
Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.
Keempat, Adam dan Hawa
terlibat secara aktif dalam drama kosmis.
Semua ayat yang mengisahkan keadaan Adam dan pasangannya dalam surga sampai
keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan
menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan
Hawa: keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Qs. 2:
35); keduanya mendapat godaan yang sama dari setan (Qs. 7: 20); sama-sama
memakan buah khuldi (Qs. 7: 22); keduanya memohon ampun dan sama-sama diampuni
Tuhan (Qs. 7: 23); dan keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan
saling membutuhkan setelah berada di bumi (Qs. 2: 187).
Fenomena ini diakui pula oleh Annemarie
Schimmel dalam penelitiannya tentang ayat-ayat yang mendeskripsikan drama kosmis bahwa tak pernah sekalipun
disebutkan dalam al-Qur’an bahwa Hawa (secara tunggal) bertanggunggjawab atas
terusirnya Adam dan Hawa dari surge.[9]
Bahkan menurut Quraish Shihab, kalaupun ada ayat yang membicarakan godaan setan
berbentuk tunggal, justru ditujukan kepada Adam seperti dalam surat Thaha ayat
120.[10]
Lebih jauh, dalam pegamatan okjektif sebagian
ilmuwan terhadap Al-quran justru memperlihatkan gambaran kepribadian yang
memukau dan simpatik dari al-Qur’an tentang wanita: Ratu Balkis—si pemimpin
teladan—Ibu Musa yang menyerahkan anaknya kepada kehendak Tuhan; Istri Fir'aun
yang menyelamatkan bayi Musa dan memohon pelindungan Allah dari penindasan
suaminya; serta Maryam wanita suci yang melahirkan Isa yang langsung menjadi
saksi akan kesuciannya.[11]
Persoalan yang mengganggu pikiran adalah
mengapa banyak terjadi bias yang menyudutkan perempuan dalam menafsirkan
Al-quran? Menurut Nasaruddin ada beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah
biasnya penafsiran al-Qur’an, dan pendekatan fiqh (penafsiran kultural) yang
bercorak patriarki yang dilakukan ulama.[12]
Fenomena ini diakui pula oleh para pengamat
kontemporer, Nasr Hamid menemukan kaum salafi tradisionalis yang mengganggap
kesetaraan laki-laki dan perempuan hanya dalam pahala dan siksa di akhirat
bukan kesetaraan sosial dengan justifikasi ayat-ayat al-Qur’an. Kemudian Budhi
Munawar melihat adanya pembedaan dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir-tafsir
klasik bahwa lelaki dalam wilayah public, sementara wanita dalam sektor
domestik; serta Karen Armstrong, seorang peneliti agama-agama Ibrahim asal
Inggris, menemukan banyak ulama yang menafsirkan al-Qur’an dengan pandangan
negatif terhadap kaum wanita.[13]
Kelima, laki-laki dan
perempuan berpotensi meraih prestasi. Beberapa ayat secara khusus yang
menegaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang
untuk meraih prestasi secara maksimum, yaitu surat ali-Imran: 195, al-Nisa:
124, al-Nahl: 97, dan Gafir: 40. Di sini diturunkan arti dari surat al-Nahl:
97: Barang siapa yang mengerjakan amal
saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Ayat tersebut mengisyaratkan konsep
kesetaraan gender yang ideal dan menegaskan bahwa prestasi individual, baik
dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli
oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh
kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan
masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih
terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.[14]
Contoh kasuistik
mengenai hal ini adalah pengamatan Jeffrey Lang yang langsung melakukan journey dan observation di Arab Saudi selama setahun penuh. Lang menemukan
masih banyak ulama di Arab Saudi yang mengklaim bahwa perempuan lebih rendah
daripada laki-laki baik dalam tataran moral, spiritual maupun intelektual.
Mereka menyatakan bahwa betapapun kerasnya wanita berusaha, maka mereka tidak
akan mampu secara intelektual bersaing dengan lelaki. Terlebih lagi mereka
memperkuat dengan postulat-postulat keagamaan secara naqli.[15]
Konklusi
Al-Qur’an
dalam memandang gender cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan-kecerdasan
manusia dalam menata pembagian peran laki-laki dan perempuan. Dengan menyadari
bahwa persoalan ini cukup penting, tetapi tidak dirinci dalam al-Qur’an. Maka
dari itu, menjadi isyarat adanya kewenangan manusia untuk menggunakan hak-hak
kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang
saling menguntungkan. Karena al-Qur’an cenderung memberikan kesempatan kepada
para ahlinya untuk menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebaik
mungkin dan saling menguntungkan di antara keduanya dalam menjalankan hak dan
kewajiban masing-masing, sehingga terwujudnya suasana serasi dan harmonis di
tengah galaunya kehidupan ini.
Referensi:
Annemarie Schimmel. (1998). Jiwaku adalah Wanita. terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
Asghar
Ali Engineer. (1994). Hak-hak
Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf.
Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Azyumardi Azra. (2000). Menuju
Masyarakat Madani.
Bandung: Rosdakarya.
Budhi Munawar-Rachman. (2004). Islam Pluralis. Jakarta:
Grafindo Persada.
Jeffrey Lang. (2002). Bahkan Malaikat Pun Bertanya. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
Karen Armstrong. (2004). Sejarah Tuhan. terj.
Zaimul Am. Bandung: Mizan.
Muhammad
Shahrur. (2004). Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan
Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq.
Nasaruddin Umar. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina.
Nasr Hamid Abu Zayd. (2003). Dekonstruksi Gender, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: PSW IAIN
SUKA.
Quraish Shihab. (1996). Wawasan
Al-Qur’an. Bandung: Mizan.
__________________. Membumikan
Al-Qur’an. Bandung: Mizan.
Waryono Abdul Ghafur. (2005). Tafsir Sosial. Yogyakarta:
Elsaq Press.
[1] M. Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq,
2004), hlm. 441.
[2] Nasaruddin
Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.
[3] Ibid.,
hlm. 35-38.
[4] Asghar Ali Engineer, Hak-hak
Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta:
Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 57.
[5] Meskipun demikian, al-Qur`an memang
berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas
perempuan. Ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial
pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan
perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis
dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan
al-Qur’an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak
akan ada kitab yang bisa efektif; jika mengabaikan konteksnya sama sekali.
Lihat: Ibid., hlm. 64.
[6] Ibid.,
hlm. 144-172.
[7] Waryono Abdul Ghafur, Tafsir
Sosial, (Yogyakarta: Elsaq Press,
2005), hlm. 109.
[8] Azyumardi Azra, Menuju
Masyarakat Madani, (Bandung:
Rosdakarya, 2000), hlm. 28.
[9] Annemarie Schimmel, Jiwaku
adalah Wanita, terj. Rahmani
Astuti, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 94.
[10] Quraish Shihab, Wawasan
Al-Qur’an, (Bandung: Mizan,1996),
hlm. 302. Lihat juga: Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung:
Mizan,1997), hlm. 272.
[11] Annemarie Schimmel, op. cit., hlm. 92-97.
[12] Nasaruddin Umar, op. cit., hlm. 281-297.
[13] Nasr Hamid Abu Zayd, Dekonstruksi
Gender, terj. Moch. Nur Ichwan dan
Moch. Syamsul Hadi, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2003), hlm. 171. Lihat juga:
Budhi Munawar-Rachman, Islam
Pluralis, (Jakarta: Grafindo
Persada, 2004), hlm. 534; Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, terj.
Zaimul Am, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 219.
[14] Nasaruddin Umar, op. cit., hlm. 247-265.
[15] Jeffrey
Lang, Bahkan Malaikat Pun Bertanya, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 167.